FLM235 Week 12 Blog
Deadlines are coming as the end of the trimester near’s. Each of the subjects major projects loom closer and closer and the pressure continues to build at uni. As I’m not an editor for the webseries…
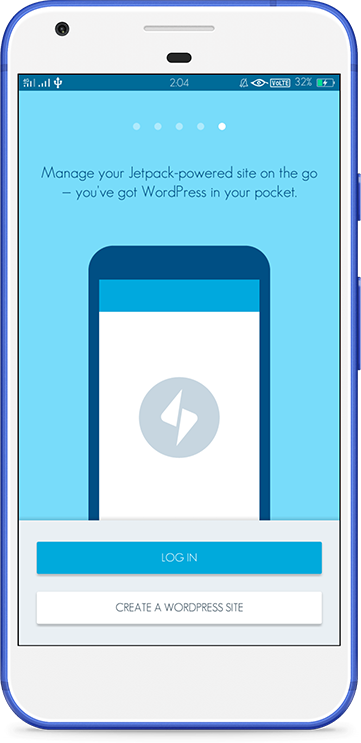
独家优惠奖金 100% 高达 1 BTC + 180 免费旋转
Sepenggal Cerita Tentang Ibu
Sebagai seorang penyintas gangguan mental, tulisanku kali ini mungkin terdengar seperti alibi yang mengada-ada atas ketidakmampuan untuk melakukan coping terhadap segala bentuk distres psikologis yang selama ini kualami. Namun sesungguhnya kuharap ini tidak terdengar sebagai pembelaan belaka.
Pengalaman konseling dan terapi dengan beberapa ahli psikologi membawaku pada perbincangan terkait kepribadian ibu. Konselor yang menanganiku di lembaga bimbingan universitas mencurigai kemungkinan ibu mengalami gangguan kepribadian. Seorang dosen mata kuliah psikodiagnostik yang mendapati hasil tes grafikku yang mencolok di tahun ketiga kuliah mengatakan bahwa ibu mungkin saja menderita bipolar. Psikolog yang membantu proses terapiku mensinyalir adanya kemungkinan ibu mengalami gangguan mood serta gangguan terkait adaptasi peran dan emosi. Semua itu membuatku sadar bahwa hampir seluruh ahli psikologi ini mempersepsikan pola perilaku ibu melalui segi kepribadian dan regulasi emosinya yang kurang baik, sehingga kupikir praduga terkait gangguan pada kedua dimensi tersebut adalah sesuatu yang wajar.
Sejujurnya early judgment tidak lebih diperkenankan dibanding penegakan diagnosis resmi. Hanya saja dalam kasusku hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Ibu menolak keras untuk menyatakan bahwa dirinya mengalami gangguan mental. Hal ini semata karena ia tidak ingin dianggap ‘gila’, bahkan oleh dirinya sendiri. Masih tertanam betul dalam ingatanku responnya ketika untuk pertama kalinya kuberitahu tentang kondisi mentalku dan gangguan psikologis yang kumiliki. Ia terduduk di kursi makan, tertawa kering dan mencemooh, kemudian menunjuk tepat di wajahku dengan jari telunjuknya yang panjang, “kamu gila?!”.
Jika boleh jujur, meskipun seringkali menyatakan ketidaksukaanku terhadap ibu secara terang-terangan, aku tidak pernah menganggap ibu sebagai orang yang sepenuhnya jahat dan tidak berusaha memengaruhi orang lain untuk menganggap ibu jahat. Sebaliknya, ibu adalah orang paling baik, setidaknya begitu pendapat sebagian besar orang yang pernah bertemu dengannya. Ia wanita yang ramah, gembira, dan penyayang. Ia banyak membantu orang-orang yang kesulitan, seperti ibu peri dalam kisah Cinderella, namun dibutuhkan sedikit kata-kata sanjungan untuk menciptakan sihirnya.
Ketika aku masih duduk di sekolah dasar dan untuk pertama kalinya memberanikan diri bercerita pada orang lain mengenai perilaku ibu terhadapku sejak kecil, tak ada satu orang pun percaya. Orang menandaiku sebagai pembohong kecil dan aku cukup sadar untuk tidak membiarkan diriku menceritakan hubunganku dengan ibu pada siapa pun sampai aku cukup dewasa untuk menyadari bahwa ada yang salah dengan perilakunya.
Sejauh ingatanku tentangnya, ibu merupakan seorang wanita pemarah. Ia tak segan-segan mengangkat tangannya untuk memukul, menampar, menonjok, atau mencubiti tubuhku hingga memar ketika aku melakukan sesuatu yang menurutnya salah. Sebelum duduk di bangku taman kanak-kanak, hampir setiap minggu kudapati luka lebam di pahaku yang gemuk. Ketika aku kesulitan tidur dan tetap terjaga hingga larut malam karena ayah pergi dinas ke luar kota, ibu menyeretku ke beranda dan mengunci pintu agar aku tidak dapat masuk ke dalam rumah. Aku meringkuk kedinginan bersama beberapa ekor kucing yang sama menderitanya denganku sampai mamah menemukanku terlelap di beranda.
Di sisi lain, ibu memaksaku untuk tetap meminum air susunya hingga usiaku mencapai lima tahun dan tak pernah sekali pun berusaha untuk menyapihku. Setelah memasuki usia empat puluhan, ibu berulang kali mengatakan bahwa payudaranya yang mulai kendur adalah akibat kesalahanku yang meminum air susunya terlalu lama. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, ibu tidak benar-benar jahat. Ia membuat masakan yang enak, memberiku uang jajan setiap hari hingga sekolah menengah atas, membelikanku tiket konser, ponsel dan laptop, serta banyak hal lainnya. Hanya saja, ambivalensi pola asuhnya adalah sebuah masalah bagi kehidupanku.
Penyelamat masa kecilku adalah nenek, ibunya ibu, yang kupanggil dengan sebutan mamah. Mamah seringkali menyelamatkanku dari amukan ibu, mengunci pintu kamarnya rapat-rapat agar aku dapat bersembunyi dalam dekapannya sementara ibu menggedornya dari luar. Ibu seringkali melampiaskan emosinya akibat tekanan di kantor kepadaku. Tak jarang ibu pulang dalam keadaan lelah dan marah, berteriak dan memaki hanya karena kesalahan kecil yang kulakukan sebagai anak-anak, kemudian menyusuiku yang menangis sesenggukan. Pernah sekali kudapati mamah menampar wajah ibu akibat memukuliku. Pada usia empat tahun, mamah membawaku ke Bandung, meninggalkan ibu dan ayah di Jakarta. Belakangan ini kutahu bahwa hal tersebut ia lakukan untuk memisahkanku dari ibu selama beberapa waktu.
Pascakematian mamah, ibu menjadi semakin pemarah. Ia seringkali melontarkan kata-kata kasar, menyebutku dengan berbagai sebutan yang tidak patut dilontarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ibu berusaha mengaturku dalam berbagai hal dan aku — yang mulai beranjak remaja — semakin sering melawan keinginannya. Pada kelas lima sekolah dasar, kudapati ibu menjalin affair dengan kepala sekolahku. Bertahun-tahun setelahnya, aku harus menanggung dampak dari hubungan tersebut.
Pada usia lima belas tahun, aku mengalami post-traumatic syndrome disorder (PTSD) akibat sebuah peristiwa traumatis yang mungkin akan kuceritakan di lain kesempatan. PTSD tersebut kemudian berkembang menjadi depresi dan gangguan kecemasan diserta halusinasi. Sebenarnya gangguan kecemasanku sudah terlihat sejak kecil dalam bentuk onychophagia yang selalu kulakukan setiap kali merasa cemas dan takut. Begitu parah hingga pakaian dan buku pelajaranku seringkali dipenuhi dengan tetesan darah. Halusinasiku muncul terutama ketika aku berada dalam kondisi stres dan tertekan. Pada malam hari yang sunyi, kudengar suara jeritan ibu memanggil namaku. Lengkingan suara ibu juga seringkali kudengar di sela-sela kegiatan perkuliahan di kelas, sebuah hal yang mustahil terjadi. Di usiaku saat ini, kusadari bahwa salah satu penyebab depresiku berakar pada hubungan antara aku dan ibu. Teriakan kemarahan ibu selalu membuatku gemetar ketakutan. Aku takut dimarahi ibu..
Dalam kapasitasku yang terbatas sebagai mahasiswi ilmu psikologi, selama ini kuanggap ibu memiliki kesulitan dalam regulasi emosi. Kemarahannya yang meluap-luap dan tidak terarah membuatku menderita sejak kecil. Kakak-kakaknya mengatakan bahwa ibu merupakan orang yang tempramen sejak kecil, namun tak ada yang berani bicara banyak mengenai perilakunya. Sesungguhnya aku meyakini bahwa tempramen hanya mewakili sebagian kecil kepingan diri ibu. Intuisiku menyatakan bahwa terdapat gangguan yang lebih universal terkait kepribadiannya. Ketika seorang dosen menuntut pandanganku terhadap kepribadian ibu dan mendorongku untuk mencari tahu lebih banyak, aku menemukan diriku menjelajah berbagai kata kunci di situs pencarian. Hal yang sesungguhnya enggan kulakukan atau berusaha kuabaikan meskipun ibu dan perilakunya telah memengaruhi kesehatan mentalku dalam dua dekade ini.
Ibu dan Maternal Narcissism
Baru-baru ini, sebuah gangguan psikologis yang disebut dengan maternal narcissism menarik atensiku. Sesuai namanya, maternal narcissism merupakan gangguan kepribadian narsistik yang dimiliki oleh seorang ibu. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5), gangguan kepribadian narsistik merupakan sebuah gangguan di mana individu memiliki perasaan berlebihan (grandiosity) terhadap diri sendiri baik dalam bentuk fantasi maupun perilaku, membutuhkan sanjungan, dan kurang empati yang dimulai sejak masa dewasa awal dan disertai oleh lima atau lebih hal-hal berikut, yaitu:
Pertemuanku dengan sebuah buku karangan Karyl McBride yang berjudul Will I Ever Be Good Enough membawaku pada kemungkinan bahwa aku memiliki seorang ibu yang narsistik. Perasaan bahwa aku tidak dicintai, tidak cukup baik bagi orang lain, tidak nyaman berada dekat dengan orang lain, dan secara terus-menerus menyangkal hal-hal positif mengenai diriku sendiri telah lama menghantui. Beruntung McBride menyertakan sebuah kuisioner yang berhubungan dengan trait-trait narsistik, di mana berdasarkan jawabanku dapat disimpulkan bahwa aku memang memiliki ibu narsistik.
Hubungan antara anak dan ibu narsistik memiliki sepuluh karakteristik yang disebut McBride sebagai The Ten Stingers, meliputi:
Perlu diketahui bahwa tulisan ini kubuat bukan untuk menyudutkan atau memprovokasi orang lain untuk membenci ibuku, sebagaimana halnya denganku. Tulisan ini juga tidak dibuat untuk menyalahkan ibuku sebagai sumber dari gangguan kesehatan mentalku. Percayalah bahwa ibuku adalah sosok wanita yang sempurna, seorang ibu yang diidam-idamkan oleh teman-temanku, namun tidak untukku.
Related posts:
Your team already learns through podcasts
Your team is listening to podcasts to keep up to date on new ideas, lessons, tools, and tips related to their work. Some of the top podcasts in the world are focussed on helping people become more…
My response about cats
This is my cats subtitle. “Cats 1.0” is published by Cecelia Story.
Is Tradecryptcoin.com legit or scam?
Tradecryptcoin is a cryptocurrency broker that allows you to buy Bitcoin (BTC) and other cryptocurrencies in more than 138 countries worldwide. If you’ve been researching where to buy Bitcoin (BTC)…